Oleh Rangga Dusy
Sebagian besar orang Jawa berusaha menyelaraskan berbagai konsep pandangan leluhurnya dengan tata cara yang diajarkan Islam. Hal ini bisa dilihat dari penyaduran orang Jawa dengan alam kodrati (dunia fana) dan alam adi kodrati (alam gaib), sehingga lahirlah ritual ruwatan Jawi-Islami yang mengusung konsep Islami namun tetap dibumbui tradisi dan adat Jawa. Seperti halnya larung (sesaji yang biasa dipersembahkan di laut atau sungai-sungai besar), kendhuri atau selamatan (melakukan doa bersama dan bersedekah sebagai ungkapan rasa syukur atau agar diberi keselamatan), dan sebagainya.
Jauh sebelum agama-agama masuk ke Jawa, sebenarnya orang Jawa sudah mengenal dan berkeyakinan bahwa ada seseorang atau sesuatu yang menjadikan dan mengatur alam serta seisinya yang layak untuk dijadikan Tuhan. Sehingga ketika agama-agama baru masuk ke Jawa, tak pernah sedikitpun terjadi bentrokan yang disebabkan dari penolakan masuknya agama tersebut. Karena sudah menjadi tabiat orang Jawa dulu, mereka tak pernah berpikir tentang imbas akulturasi ataupun asimilasi yang sehingga bisa melunturkan adat-istiadat yang sudah terlaku turun temurun.
Pola berpikir seperti ini tak lain merupakan upaya manusia untuk memahami keberadaannya diantara sesama makhluk yang tersebar di jagat raya ini, lantas membawanya ke suatu pengembaraan yang tak pernah berhenti. Sehingga ketika ada hal-hal baru yang mereka anggap bisa menunjukan jalan menuju titik cerah perjalanannya, pastilah mereka ikuti. Sebagaimana pengembaraan iman yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim as. ketika pertama kali beliau keluar dari goa persembunyiannya. Saat melihat bintang, beliau berkata: “Inilah Tuhanku,” kata Nabi Ibrahim. Namun, ketika tenggelam beliau berkata, “Tuhanku bukanlah yang tenggelam.” Kemudian ketika bulan muncul, maka beliau berpikir bahwa Tuhan adalah bulan. Demikian pula ketika bulan tenggelam dan terbitlah matahari, beliau beranggapan bahwa Tuhan adalah matahari, karena lebih besar dan terang. Setelah semua hilang dan redup silih berganti, terbukalah beliau bahwa Tuhan bukanlah seperti yang dipersekutukan para kaumnya (Lihat QS. Al-An’am 76-69).
Begitu pula yang terjadi pada orang Jawa pra-agama. Dari pengembaraan mereka mencari kebenaran Sang Hyang Murbaning Dumadi, muncullah beberapa keyakinan seperti halnya animisme dinamisme, yaitu penyembahan terhadap roh dan benda-benda yang memberi tuah dan memiliki kekuatan. Kepercayaan seperti ini terjadi, karena mereka berfikir bahwa adanya perjalanan alam dan isinya ini tentu ada yang menciptakan dan mengatur agar terjadi stabilitas antar sesama. Faktor seperti inilah yang menjadikan masyarakat Jawa dapat cepat beradaptasi dengan kedatangan agama-agama yang baru.
Cara berinteraksi budaya Jawa dengan Islam tergolong unik. Dalam penyebutan apapun yang diyakini suci atau dipandang mulia, mereka memberikan sebuah apresiasi maha tinggi, sebagaimana penyebutan Tuhan dengan Gusti Allah Ingkang Murbaning Dumadi dan juga keyakinan bahwa Rasul Saw sangat dekat dengan Allah, sehingga hampir dalam semua upacara ritual mereka selalu menyebutkan nama Allah Kang Moho Kuwaos dan Kanjeng Nabi Muhammad ingkang sumare wonten siti Madinah (Koentjaraningrat)
Peng-islam-an masyarakat Jawa tidaklah terlalu sulit. Karena, selain penyebar Islam kala itu kebanyakan adalah kalangan Islam sufi yang tidak membekali diri dengan ilmu kepemimpinan dan tidak menginginkan kepemimpinan, juga dilatar belakangi jiwa seni dan sastra masyarakat Jawa. Sehingga ketika para Walisongo dengan dipandegani Sunan Kalijaga menyebarkan agama dengan media seni wayang, gamelan, dan sastra Arab, yang dibaurkan dengan budaya Jawa, dapat diterima di tengah-tengah masyarakat Jawa.
Tingginya nilai seni dan sastra bagi masyarakat Jawa telah ada sebelum agama Islam masuk. Dengan bukti adanya candi dan relif-relif kuno, serta banyaknya kaligrafi ukir dan serat yang dibuat oleh para pujangga. Setelah Islam masuk, kesenian dan kesustraan Jawa mulai dikolaborasikan oleh Walisongo. Dimulai pertama kali dengan wujudnya seni wayang dan gamelan yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga tersebut, berlanjut dengan sastra yang diramu oleh Sunan Kalijaga dalam media dakwahnya.
Sesaat setelah kolonial Belanda merangsek masuk ke Indonesia, kesenian dan kesustraan Jawa mulai tersisihkan. Karena kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kolonial saat itu memang menyulitkan masyarakat untuk berkutat di bidang seni dan sastra. Hingga pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram yang merasa prihatin dengan kondisi demikian. Kala itu, sedikit demi sedikit Sultan Agung mulai membuat strategi guna merangsang para pujangga Jawa untuk mengimprovisasikan sastra. Guna menggairahkan jiwa seni dan sastra, Sultan Agung mencoba membaurkan sastra Arab dari lingkungan pesantren dan sastra Jawa dari budaya kejawen. Akhirnya, strategi Sultan Agung itu berhasil, sehingga muncullah hasil kreatifitas para pujangga yang dituangkan dalam bentuk tembang macapatan dan serat seperti halnya serat centhini, babad tanah demak, dan lain sebagainya.
Kemudian kala seni dan sastra Jawa mulai bangkit lagi dengan pembauran berbagai bahasa dan budaya, maka timbullah sastra Jawa yang digubah kembali dengan menyatukan sastra Jawa kuno yang diperhalus dengan unsur-unsur yang berbau sufistik. Sebagaimana ramalan-ramalan Ranggawarsita tentang kejadian alam yang disarikan dari al Quran dan Hadis.
Terahir, sebagaimana pesan dalam layang Joyoboyo; “Tumindakho kang djudjor marang roso siro. Awet roso kuwi tjahyoning Gusti kang moho sutji. Kang manggon ono ing rogo siro, odjo diregetake.” Arti bebasnya kurang lebih demikian; berbuatlah jujur pada dirimu sendiri, karena dari situlah munculnya cahaya Tuhan yang Maha Suci, yang menetap dalam ragamu. Janganlah kau kotori.
Sebagian besar orang Jawa berusaha menyelaraskan berbagai konsep pandangan leluhurnya dengan tata cara yang diajarkan Islam. Hal ini bisa dilihat dari penyaduran orang Jawa dengan alam kodrati (dunia fana) dan alam adi kodrati (alam gaib), sehingga lahirlah ritual ruwatan Jawi-Islami yang mengusung konsep Islami namun tetap dibumbui tradisi dan adat Jawa. Seperti halnya larung (sesaji yang biasa dipersembahkan di laut atau sungai-sungai besar), kendhuri atau selamatan (melakukan doa bersama dan bersedekah sebagai ungkapan rasa syukur atau agar diberi keselamatan), dan sebagainya.
Jauh sebelum agama-agama masuk ke Jawa, sebenarnya orang Jawa sudah mengenal dan berkeyakinan bahwa ada seseorang atau sesuatu yang menjadikan dan mengatur alam serta seisinya yang layak untuk dijadikan Tuhan. Sehingga ketika agama-agama baru masuk ke Jawa, tak pernah sedikitpun terjadi bentrokan yang disebabkan dari penolakan masuknya agama tersebut. Karena sudah menjadi tabiat orang Jawa dulu, mereka tak pernah berpikir tentang imbas akulturasi ataupun asimilasi yang sehingga bisa melunturkan adat-istiadat yang sudah terlaku turun temurun.
Pola berpikir seperti ini tak lain merupakan upaya manusia untuk memahami keberadaannya diantara sesama makhluk yang tersebar di jagat raya ini, lantas membawanya ke suatu pengembaraan yang tak pernah berhenti. Sehingga ketika ada hal-hal baru yang mereka anggap bisa menunjukan jalan menuju titik cerah perjalanannya, pastilah mereka ikuti. Sebagaimana pengembaraan iman yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim as. ketika pertama kali beliau keluar dari goa persembunyiannya. Saat melihat bintang, beliau berkata: “Inilah Tuhanku,” kata Nabi Ibrahim. Namun, ketika tenggelam beliau berkata, “Tuhanku bukanlah yang tenggelam.” Kemudian ketika bulan muncul, maka beliau berpikir bahwa Tuhan adalah bulan. Demikian pula ketika bulan tenggelam dan terbitlah matahari, beliau beranggapan bahwa Tuhan adalah matahari, karena lebih besar dan terang. Setelah semua hilang dan redup silih berganti, terbukalah beliau bahwa Tuhan bukanlah seperti yang dipersekutukan para kaumnya (Lihat QS. Al-An’am 76-69).
Begitu pula yang terjadi pada orang Jawa pra-agama. Dari pengembaraan mereka mencari kebenaran Sang Hyang Murbaning Dumadi, muncullah beberapa keyakinan seperti halnya animisme dinamisme, yaitu penyembahan terhadap roh dan benda-benda yang memberi tuah dan memiliki kekuatan. Kepercayaan seperti ini terjadi, karena mereka berfikir bahwa adanya perjalanan alam dan isinya ini tentu ada yang menciptakan dan mengatur agar terjadi stabilitas antar sesama. Faktor seperti inilah yang menjadikan masyarakat Jawa dapat cepat beradaptasi dengan kedatangan agama-agama yang baru.
Cara berinteraksi budaya Jawa dengan Islam tergolong unik. Dalam penyebutan apapun yang diyakini suci atau dipandang mulia, mereka memberikan sebuah apresiasi maha tinggi, sebagaimana penyebutan Tuhan dengan Gusti Allah Ingkang Murbaning Dumadi dan juga keyakinan bahwa Rasul Saw sangat dekat dengan Allah, sehingga hampir dalam semua upacara ritual mereka selalu menyebutkan nama Allah Kang Moho Kuwaos dan Kanjeng Nabi Muhammad ingkang sumare wonten siti Madinah (Koentjaraningrat)
Peng-islam-an masyarakat Jawa tidaklah terlalu sulit. Karena, selain penyebar Islam kala itu kebanyakan adalah kalangan Islam sufi yang tidak membekali diri dengan ilmu kepemimpinan dan tidak menginginkan kepemimpinan, juga dilatar belakangi jiwa seni dan sastra masyarakat Jawa. Sehingga ketika para Walisongo dengan dipandegani Sunan Kalijaga menyebarkan agama dengan media seni wayang, gamelan, dan sastra Arab, yang dibaurkan dengan budaya Jawa, dapat diterima di tengah-tengah masyarakat Jawa.
Tingginya nilai seni dan sastra bagi masyarakat Jawa telah ada sebelum agama Islam masuk. Dengan bukti adanya candi dan relif-relif kuno, serta banyaknya kaligrafi ukir dan serat yang dibuat oleh para pujangga. Setelah Islam masuk, kesenian dan kesustraan Jawa mulai dikolaborasikan oleh Walisongo. Dimulai pertama kali dengan wujudnya seni wayang dan gamelan yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga tersebut, berlanjut dengan sastra yang diramu oleh Sunan Kalijaga dalam media dakwahnya.
Sesaat setelah kolonial Belanda merangsek masuk ke Indonesia, kesenian dan kesustraan Jawa mulai tersisihkan. Karena kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kolonial saat itu memang menyulitkan masyarakat untuk berkutat di bidang seni dan sastra. Hingga pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram yang merasa prihatin dengan kondisi demikian. Kala itu, sedikit demi sedikit Sultan Agung mulai membuat strategi guna merangsang para pujangga Jawa untuk mengimprovisasikan sastra. Guna menggairahkan jiwa seni dan sastra, Sultan Agung mencoba membaurkan sastra Arab dari lingkungan pesantren dan sastra Jawa dari budaya kejawen. Akhirnya, strategi Sultan Agung itu berhasil, sehingga muncullah hasil kreatifitas para pujangga yang dituangkan dalam bentuk tembang macapatan dan serat seperti halnya serat centhini, babad tanah demak, dan lain sebagainya.
Kemudian kala seni dan sastra Jawa mulai bangkit lagi dengan pembauran berbagai bahasa dan budaya, maka timbullah sastra Jawa yang digubah kembali dengan menyatukan sastra Jawa kuno yang diperhalus dengan unsur-unsur yang berbau sufistik. Sebagaimana ramalan-ramalan Ranggawarsita tentang kejadian alam yang disarikan dari al Quran dan Hadis.
Terahir, sebagaimana pesan dalam layang Joyoboyo; “Tumindakho kang djudjor marang roso siro. Awet roso kuwi tjahyoning Gusti kang moho sutji. Kang manggon ono ing rogo siro, odjo diregetake.” Arti bebasnya kurang lebih demikian; berbuatlah jujur pada dirimu sendiri, karena dari situlah munculnya cahaya Tuhan yang Maha Suci, yang menetap dalam ragamu. Janganlah kau kotori.

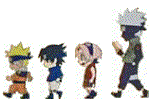

0 comments:
Post a Comment